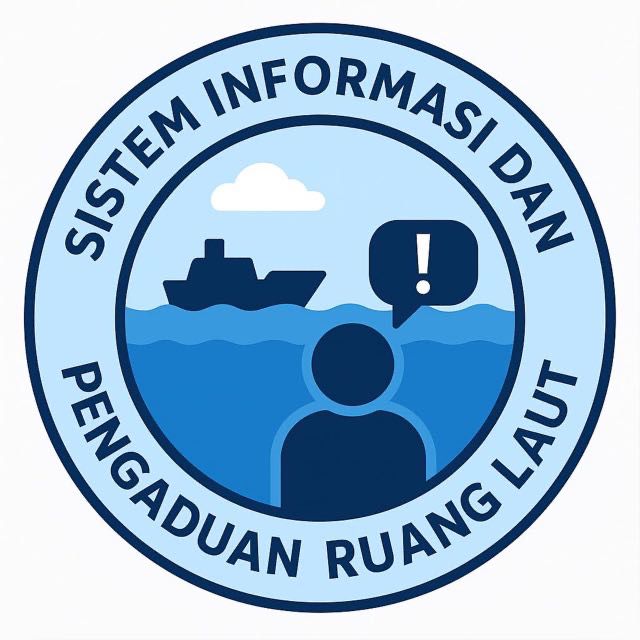Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi kepulauan dengan luas perairan sekitar 7.450.266,11 km (BIG, 2021), panjang garis pantai 6.841,86 km (BIG, 2021) dan memiliki 1.572 pulau (BIG, 2022) dimana terdapat 3 pulau pulau kecil terluar yakni pulau Dolongan, Pulau Lingayan dan Pulau Salando. Provinsi Sulawesi tengah memiliki 13 kabupaten / kota dimana 12 kabupaten memiliki perairan laut dan hidup bermukim di sepanjang pesisir. Dengan potensi tersebut maka, di butuhkan tanggung jawab dan peran secara bersama antara masyarakat, lembaga/kelompok dan pemerintah dalam pengelolaan secara bijak untuk keberlanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal.
Pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.
Wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang satu sama lain saling berkait dan tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa ekosistem lainnya. Selain itu wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di lahan atas (upland areas) maupun laut lepas (oceans). Kelembagaan masyarakat mempunyai fungsi dan peran yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yakni sebagai penerima manfaat dari sumberdaya alam juga sebagai penjaga laut dari segala bentuk kerusakan lingkungan.
Bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pembangunan pengelolaan wilayah pesisir. Suatu proses kesadaran seseorang dalam pengelolaan tentang pesisir dipengaruhi oleh pengalaman dalam pengelolaan wilayah pesisir. Keterlibatan seseorang dalam pengelolaan wilayah pesisir mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan sampai evaluasi maka akan mempengaruhi perilaku persepsi seseorang. Program pengelolaan wilayah pesisir wajib melibatkan masyarakat sebagai pengguna utama sumber daya. Selain itu pemahaman masyarakat mengenai pesisir terhadap sumber daya yang ada lebih mengarah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tanpa memahami nilai sumber daya dengan mengabaikan dampak ekologis, sehingga pemanfaatan cenderung bersifat eksploitatif, perusakan dan pencemaran ekosistem.
Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbagi menjadi tiga yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Masyarakat hukum adat (MHA) adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi tersebut maka terdapat empat syarat utama masyarakat disebut sebagai MHA.
Masyarakat lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. Berbeda dari MHA, masyarakat lokal tidak memiliki pranata pemerintahan adat secara turun -temurun diterapkan berdasarkan nilai-nilai adat dan asal-usulnya. Kata “lokal” sendiri menegaskan bahwa batasan spasial atau lokasi geografis merupakan entitas utama masyarakat ini.
Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
Salah satu bentuk solusi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir adalah melalui lembaga masyarakat (pesisir) dengan pendekatan pengembangan kawasan. Program Pengembangan lembaga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan menghasilkan peningkatan sumber daya manusia, prasarana dan produksi. Pengembangan kawasan pesisir di butuhkan dikelolah secara bijak dan memperhatikan kearifan local, kebiasaan turun temurun masyarakat juga berpengaruh dalam perlindungan pelestarian laut dan pesisir. Selain itu menjaga dan pelestarian ekosistem laut dan pesisir adalah kewajiban semua lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang bermukim di sepanjang pesisir laut. Kerja bersama seluruh komponen masyarakat terutama para kelompok masyarakat yang bersama sama bergotong royong menjaga ekosistem di harapkan menjadi bagian terdepan untuk keberlanjutan ekosistem laut.
Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 12 kabupaten dimana sepanjang pesisir banyak terdapat pemukiman, dan tingginya aktifitas penduduk. Tingginya aktifitas juga berdampak pada eksplorasi, degradasi, pencemaran dan kerusakan lingkungan di antaranya terumbu karang, mangrove dan pencemaran laut.
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
Pengelolaan Sumberdaya alam pesisir pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Tujuan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut adalah dengan membangkitkan kesadaran masyarakat (public awarness) disamping melakukan proses-proses partisipasi dan kolaborasi/kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir yang tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan. Strategi ekosistem pesisir dan laut adalah Untuk mengimplementasikan
Pengelolaan kebijakan dan program maka setidaknya ada lima strategi yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan
2. Mengacu pada Prinsip-prinsip dasar dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu
3. Proses Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu
4. Elemen dan Struktur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu
5. Penerapan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu di tataran praktis kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.
Berdasarkan arah dan kebijakan dari pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang telah ditegaskan dalam GBHN, maka perlu ditetapkan pokok-pokok kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Pokok pokok kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan yakni :
1. Kebijakan menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional,
2. Mendayagunakan potensi laut dan dasar laut,
3. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan,
4. Mengembangkan potensi berbagai industri kelautan nasional dan penyebarannya di seluruh wilayah tanah air,
5. Memenuhi kebutuhan data dan informasi kelautan serta memadukan dan mengembangkannya dalam suatu jaringan sistem informasi kelautan dan
6. Mempertahankan daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Gambar. Kegiatan Bimtek Peran Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Gambar. Kunjungan ke "Bank Sampah Navoe" Kelompok Masyakarat Mandiri
Gambar. Kunjungan Survey Vegetasi Pantai bersama Kelompok Masyarakat dan Tim DitP4K KKP